Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Setiap musim panen, pemandangan yang sama berulang di banyak sentra padi Indonesia: gundukan jerami dibakar di tepi sawah. Langit mengabu, udara mengental oleh asap, padahal yang terbakar itu sejatinya adalah sumber energi dan devisa yang luar biasa besar. Di tengah tekanan krisis energi, subsidi BBM, dan komitmen net zero emission, pertanyaannya sederhana: sampai kapan jerami kita biarkan jadi asap, bukan jadi bahan bakar?
Lautan Jerami yang Selama Ini Seperti Terabaikan
Indonesia memproduksi lebih dari 50 juta ton gabah per tahun. Dari setiap satu ton gabah, kira-kira ada satu hingga satu setengah ton jerami yang dihasilkan. Artinya, secara nasional kita berbicara tentang 80 juta ton hingga 120 juta ton jerami padi per tahun.
Bila dihitung kandungan energinya, jerami yang secara teknis dan ekologis aman untuk diambil (sekitar 25 juta ton hingga 60 juta ton per tahun) setara dengan 350-900 petajoule energi - jumlah yang signifikan dibanding kebutuhan BBM nasional sebesar 23.213,2 petajoule (PJ) di tahun 2023.
Namun, realitas di lapangan berbeda jauh. Di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia, baru sekitar 20 persen jerami yang dimanfaatkan (pakan, media jamur, kertas, bahan bakar kecil-kecilan, kompos).
Sisanya dibiarkan membusuk sembarangan atau dibakar terbuka. Padahal, bila dikelola sebagai biomassa, jerami bisa menjadi bahan baku penting untuk listrik, panas industri, biogas, hingga biofuel generasi kedua.
Sisi Lain Jerami: Bukan Sekadar Limbah
Secara teknis, jerami padi adalah biomassa lignoselulosa - tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Ini membuat jerami sebagai bahan kaya energi dengan nilai kalor sekitar 14-16 MJ/kg, mirip banyak jenis biomassa lain. Dengan demikian, cocok untuk berbagai teknologi: bisa dikonversi menjadi listrik, panas, gas sintesis (syngas), minyak pirolisis, etanol selulosa, maupun biogas.
Namun ada tantangan khas jerami padi, seperti kadar abu dan silika tinggi yang dapat menyebabkan slagging, fouling, dan korosi pada boiler, serta penggumpalan pada gasifier bila desainnya tidak sesuai. Jerami juga memiliki kandungan logam alkali (K, Na, Cl) tinggi, dengan efek menurunkan titik leleh abu sehingga mudah membentuk deposit lengket.
Satu hal lagi, massa jenis Jerami yang rendah (bulky), sehingga biaya angkut mahal kalau tidak dipres atau dipellet. Artinya, jerami itu potensial, tetapi perlu teknologi dan rekayasa sistem yang tepat. Tidak bisa sekadar "dimasukkan ke tungku" begitu saja.
Kalau Jerami Diambil dari Sawah, Apa Dampaknya?
Selama ini, banyak agronom dan peneliti menyerukan pentingnya pengembalian jerami ke sawah. Alasannya kuat, pertama jerami mengandung sebagian besar kalium (K) dan sebagian nitrogen (N) serta fosfor (P) yang diserap tanaman; kedua pengembalian jerami membantu menjaga bahan organik tanah, struktur tanah, dan kemampuan tanah menahan air.
Jika jerami diambil habis-habisan tanpa kompensasi, tanah akan "kurus": bahan organik turun, kebutuhan pupuk kimia naik, dan produktivitas jangka panjang bisa terancam.
Di sisi lain, praktik membenamkan jerami di sawah tergenang air juga punya masalah: emisi metana (CH₄) meningkat karena jerami menjadi sumber karbon mudah terdekomposisi di lingkungan anaerob. Dari sudut pandang iklim, ini bukan kabar baik.
Di sinilah bioenergi bisa menjadi solusi win-win, asalkan dikelola cermat. Prinsipnya (i) Jangan 100% jerami diambil. Misalnya hanya 50%-70% jerami yang dikumpulkan, sisanya tetap di sawah sebagai penutup tanah; (ii) Kembalikan nutrien dan karbon melalui abu, kompos, digestate biogas, atau biochar ke lahan; (iii) Kombinasikan dengan pengelolaan air (misalnya alternate wetting and drying) untuk menekan emisi metana.
Artinya, jerami untuk energi harus menjadi bagian dari strategi pengelolaan residu yang terpadu, bukan sekadar "dipindahkan masalahnya dari sawah ke pabrik".
Dari Sawah ke Tangki: Ragam Teknologi Konversi
Ada beberapa jalur utama untuk mengubah jerami menjadi energi atau bahan bakar, seperti (1) Pembakaran langsung dan co-firing, Teknologi ini paling matang, namun butuh desain boiler yang sanggup menangani abu dan silika tinggi; (2) Gasifikasi, Jerami diubah menjadi gas sintesis (campuran CO, H₂, CH₄) dengan udara atau oksigen terbatas. Gas ini bisa digunakan untuk listrik (mesin gas/turbin) atau diolah lebih lanjut. Isunya adalah pembersihan tar dan pengendalian abu;
(3) Pirolisis dan torrefaction, pemanasan dalam kondisi tanpa oksigen untuk menghasilkan bio-oil, biochar, dan gas. Bio-oil bisa jadi bahan bakar boiler atau di-upgrade di kilang; biochar bisa dikembalikan ke tanah untuk memperbaiki kualitas tanah dan menyimpan karbon.
Rute lainnya adalah rute biokimia dan biologi seperti (1) Etanol generasi kedua (2G) dan (2) Biogas / biomethane. Pada rute Etanol Generasi Kedua, jerami "diurai" menjadi gula sederhana dan difermentasi menjadi etanol. Salah satu teknologi contoh adalah sunliquid® dari Clariant.
Konsep ini diklaim mampu menghasilkan pengurangan emisi hingga sekitar 90-95% dibanding bensin fosil, dan dikategorikan sebagai advanced biofuel di Eropa. Meskipun demikian, demo plant-nya sendiri pada saat in terpaksa ditutup karena permasalahan teknis.
Untuk rute biogas/biomethane, Jerami dicacah dan diberi perlakuan awal, dapat dicerna secara anaerob untuk menghasilkan biogas. Setelah dimurnikan, biogas menjadi biomethane yang dapat disuntikkan ke jaringan gas atau dipakai sebagai bahan bakar transportasi. Limbah padat/cairnya kembali menjadi pupuk organik untuk sawah.
Setiap rute mempunyai keunggulan dan kelemahannya. Pembakaran dan co-firing lebih sederhana, biogas menarik di lokasi dengan ternak dan sawah sekaligus, sementara etanol 2G dan rute sintetik lainnya menawarkan nilai tambah lebih tinggi, tetapi dengan investasi dan risiko teknis yang lebih besar.
Menjahit Ekosistem Bisnis: dari Petani ke Kilang
Apapun pilihan teknologinya, kunci sukses pemanfaatan jerami sebagai energi ada pada ekosistem bisnis dan kebijakan. Beberapa pelajaran penting dari proyek-proyek di Eropa dan China:
• Teknologi saja tidak cukup. Ada pabrik skala besar yang secara teknis berhasil dibangun, tetapi kesulitan beroperasi stabil dan menguntungkan karena pasokan jerami tidak konsisten, kualitas bahan baku bervariasi, dan kebijakan perubahan.
• Kontrak dengan petani dan koperasi menjadi fondasi. Siapa mengumpulkan jerami? Dengan harga berapa per ton? Siapa yang menanggung biaya baling, transportasi, dan penyimpanan? Tanpa model bisnis yang jelas dan menarik bagi petani, pasokan akan rapuh.
• Kebijakan harus memberikan sinyal jangka panjang. Di Eropa, biofuel jerami masuk kategori advanced dan mendapat insentif seperti kuota khusus, penghitungan ganda, dan dukungan pendanaan. Indonesia perlu desain kebijakan serupa bila serius ingin membangun industri ini.
Dalam konteks Indonesia, pemain industri bisa mengambil peran sebagai offtaker utama dan pemilik pabrik, sementara jerami dipasok oleh jaringan koperasi petani dan BUMDes. Pemerintah menyediakan payung kebijakan: mandat campuran biofuel lanjutan, skema harga yang adil, dukungan pembiayaan hijau, dan aturan pengelolaan residu yang menjaga kesehatan tanah.
Sekali lagi, dibutuhkan kebijakan, komitmen dan insentif yang jelas dari semua pemangku kepentingan untuk implementasinya dengan mempertimbangkan daya dukung ekonomi negara.
Dari Jerami Menjadi Strategi Nasional
Jika dikelola dengan benar, jerami padi bisa mengisi banyak kotak sekaligus: mengurangi polusi asap bakar, menekan emisi gas rumah kaca, mengurangi impor BBM, membuka pasar baru bagi petani, dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Pilihan di depan kita bukan sekadar "jerami dibakar atau tidak", tetapi apakah kita siap menjadikannya bagian dari strategi energi dan industrialisasi Indonesia. Lautan jerami yang hari ini menjadi asap bisa menjadi pondasi ekosistem bioenergi yang modern, asalkan teknologi, kebijakan, dan model bisnis dijahit dengan visi jangka panjang.
(miq/miq)































:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/bola/watermark-color-landscape-new.png,1125,20,0)/kly-media-production/medias/5339674/original/047240900_1757081733-20250904AA_Timnas_Indonesia_vs_China_Taipei-08.JPG)
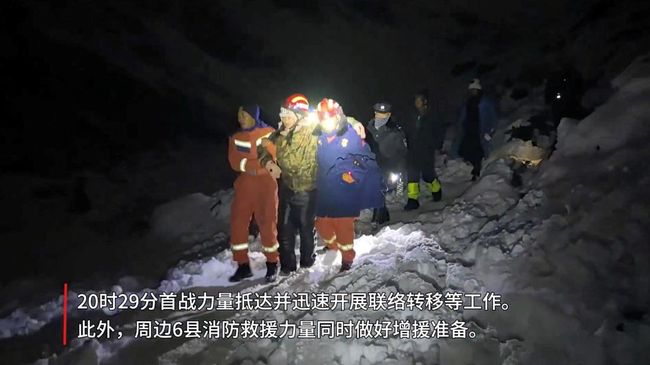





:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5165907/original/040062200_1742202626-3.jpg)

:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/bola/watermark-color-landscape-new.png,1125,20,0)/kly-media-production/medias/5342106/original/027230600_1757384899-Timnas_Indonesia_vs_Lebanon_-20.jpg)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5392922/original/058076400_1761535740-ATK_Bolanet_BRI_Super_League_2025_26_Persib_vs_Persis_Solo.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5248785/original/070439600_1749619357-000_49TH2TP.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5395563/original/063153100_1761711808-ATK_Bolanet_BRI_SUPER_LEAGUE_BIG_MATCH__2_.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5144845/original/022421200_1740645722-Timnas_Indonesia_-_Trio_Calon_Pemain_Naturalisasi_Timnas_copy.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5362971/original/078040500_1758878372-Persita_Tangerang_Vs_Persib_Bandung.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5362119/original/035085500_1758837955-Calvin-Verdonk-Europa-League.jpg)