Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Kasus pemberhentian guru di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu sempat membuat publik terbelah. Banyak yang berempati kepada para guru dan tidak sedikit pula yang mengkritik kebijakan pungutan yang terjadi.
Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan dengan mengambil langkah rehabilitasi. Namun di balik keputusan tersebut, terdapat persoalan serius yang perlu dibahas secara lebih luas. Praktik-praktik serupa terjadi hampir di seluruh institusi pendidikan di tanah air.
Kasus ini bermula dari pungutan yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada orang tua murid untuk membayar honor guru yang belum mendapat gaji. Tindakan yang diambil oleh guru tersebut sebagai upaya kreatif untuk membantu tenaga honorer yang tidak memiliki kepastian pendapatan. Namun jika ditelusuri lebih jauh, terdapat sejumlah aturan yang dilanggar khususnya berkaitan dengan tata kelola keuangan negara.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggarannya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Norma ini adalah koridor untuk memastikan setiap pengeluaran pemerintah harus memiliki pos anggaran yang jelas.
Dalam konteks ini, terjadi keterkaitan antara kepala sekolah dan guru honorer dalam Hukum Keuangan Negara. Kepala sekolah bertindak selaku pejabat yang tindakannya berakibat pada pengeluaran daerah yaitu melakukan perikatan dengan guru honorer.
Guru honorer berperan sebagai supplier bagi pemerintah. Supplier dalam kacamata keuangan negara adalah pihak yang berhak menerima pembayaran dari APBN/APBD atas suatu beban, dapat berupa penyedia barang/jasa, pegawai, atau pihak lain yang menerima pembayaran atas transaksi pemerintah.
Selayaknya perikatan tersebut sudah memiliki alokasi anggaran untuk pembayarannya. Seandainya dalam perikatan tersebut tidak tersedia alokasi pendanaan dari APBD maka dapat dipastikan telah terjadi penyimpangan terhadap UU Perbendaharaan Negara.
Pengecualian bisa diberikan bagi unit pemerintah dengan status sebagai BLU atau BLUD. BLU/BLUD dapat dikecualikan karena mereka memiliki sumber pendapatan sendiri dan dalam penggunaan pendapatan tersebut terdapat komponen gaji bagi pegawai yang dimiliki.
Pelanggaran paling mendasar dalam kasus Luwu adalah adanya hubungan kerja tanpa dukungan anggaran resmi. Realitas pahitnya fenomena semacam ini terjadi hampir di seluruh sekolah negeri di Indonesia. Guru honorer direkrut oleh sekolah, tetapi anggaran untuk menggaji mereka tidak tersedia di APBD. Akibatnya sekolah pun mencari jalan pintas melalui sumbangan, kontribusi, atau pungutan dari orang tua murid.
Sekolah negeri jenjang dasar hingga menengah pada dasarnya tidak boleh memungut uang dari peserta didik. Larangan ini ditegaskan kembali dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
Dalam Permendikbud tersebut pada Pasal 12 huruf b berisi larangan bagi Komite Sekolah untuk melakukan Pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya. Masih dalam regulasi yang sama secara tegas terjadi pemisahan makna antara sumbangan, bantuan, dan pungutan.
Bantuan Pendidikan dimaknai sebagai pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
Pungutan Pendidikan dimaknai sebagai penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.
Sedangkan Sumbangan Pendidikan dimaknai dengan pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.
Perbedaan signifikan antara pungutan dan sumbangan terletak pada sifat, jumlah, serta waktu pemberiannya. Ketika pemberian tersebut ditentukan besarannya, kapan waktunya, serta menjadi kewajiban bagi seluruh peserta didik maka dimaknai sebagai pungutan. Meski dilakukan dengan niat membantu guru, pungutan tetaplah pungutan. Terdapat aturan yang secara tegas melarangnya.
Secara popularitas memang menjatuhkan kesalahan ke para guru bagai melawan arus suara khalayak. Jika hanya melihat kasus ini secara mikro tentu saja simpati akan diberikan kepada guru-guru tersebut. Namun apabila kita melihat dari kacamata yang lebih lebar mungkin akan terlihat ada beberapa praktik yang harus dikoreksi di masa yang akan datang.
Kasus di Luwu memberikan gambaran tentang sistem pengelolaan SDM yang tidak terpusat dan tidak terencana di lingkup daerah. Selama ini rekrutmen honorer terjadi di tingkat sekolah. Kepala sekolah kerap merasa kekurangan tenaga pendidik sehingga menambah guru honorer tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah. Potret ini yang seringkali terlewatkan oleh pemda dalam mengalokasikan belanja pegawai yang memadai bagi guru dengan status nonASN.
Idealnya rekrutmen guru honorer dilakukan terpusat pada masing-masing pemda dengan melibatkan minimal tiga pihak yaitu Badan Pengelola SDM, Badan Keuangan Daerah, dan Dinas Pendidikan. Tiga unsur ini perlu duduk bersama untuk menilai kebutuhan sekolah, ketersediaan formasi, serta kemampuan anggaran. Tanpa prosedur ini, sekolah akan terus terjebak dalam pola yang sama yaitu menambah guru tanpa anggaran lalu meminta pungutan kepada orang tua murid.
Bantuan operasional pendidikan sebenarnya telah disediakan oleh pemerintah untuk membantu sekolah dalam menutup kebutuhan operasional. Namun bantuan operasional tersebut memiliki sejumlah pembatasan dalam penggunaannya.
Meski ada alokasi hingga 40% untuk honor, hanya guru yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dapat dibayar melalui skema tersebut. Guru honorer yang tidak tercatat otomatis berada di luar skema. Inilah salah satu pemicu munculnya pungutan khususnya jika sekolah memiliki pegawai yang berstatus nonASN dan tidak tercantum dalam database.
Dalam hal terjadi kebutuhan operasional sekolah lebih besar daripada dana bantuan operasional yang diterima maka terjadi kecenderungan untuk menarik pungutan melalui pelibatan Komite Sekolah.
Seharusnya pemda dapat mengambil peran lebih besar dalam menyikapi hal tersebut. Pemda bisa mengalokasikan pendanaan tambahan melalui anggaran sekolah, baik melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekolah maupun bantuan operasional tambahan yang bersumber dari APBD. Cara tersebut adalah solusi bagi sekolah agar tidak lagi menjadikan orang tua murid sebagai sumber dana darurat.
Keputusan Presiden Prabowo untuk merehabilitasi para guru memang menyelesaikan masalah jangka pendek. Namun kasus ini seharusnya menjadi catatan bagi seluruh pengambil kebijakan, baik di pusat maupun daerah.
Pemerintah perlu memastikan bahwa rekrutmen guru honorer dilakukan secara terencana dan terpusat. Selanjutnya dalam hal terjadi kebutuhan pegawai nonASN agar dapat dipastikan bahwa anggaran untuk membayar pegawai telah tersedia sebelum terjadi perikatan antara sekolah dengan guru. Dan yang terakhir adanya dukungan pendanaan oleh pemda jika terjadi defisit biaya operasional.
Jika pembenahan tidak dilakukan, kasus Luwu hanya akan menjadi satu dari sekian banyak contoh yang terus berulang. Pihak yang dirugikan dalam hal tidak terjadi perbaikan tata kelola adalah orang tua/wali murid yang akan tergencet dengan berbagai pungutan di sekolah.
Kasus ini memang harus diselesaikan secara tuntas dengan melihat berbagai aspek yang ada. Jika penyelesaiannya hanya kasus per kasus dan pada isu yang sifatnya mikro maka jangan kaget jika suatu saat akan muncul keriuhan baru berupa protes dari orang tua murid atas munculnya pungutan-pungutan dengan berbagai dalih di sekolah.
(miq/miq)































:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/bola/watermark-color-landscape-new.png,1125,20,0)/kly-media-production/medias/5339674/original/047240900_1757081733-20250904AA_Timnas_Indonesia_vs_China_Taipei-08.JPG)
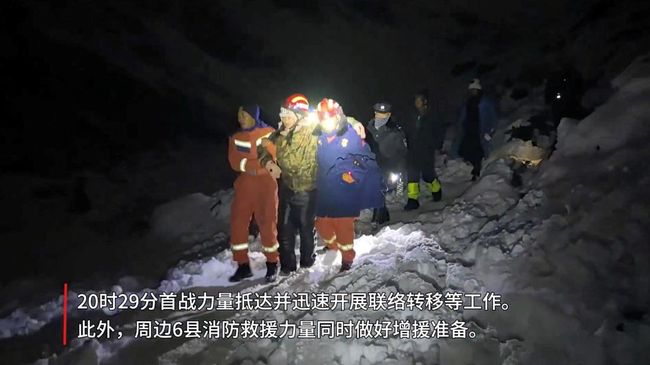





:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5165907/original/040062200_1742202626-3.jpg)

:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/bola/watermark-color-landscape-new.png,1125,20,0)/kly-media-production/medias/5342106/original/027230600_1757384899-Timnas_Indonesia_vs_Lebanon_-20.jpg)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5392922/original/058076400_1761535740-ATK_Bolanet_BRI_Super_League_2025_26_Persib_vs_Persis_Solo.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5248785/original/070439600_1749619357-000_49TH2TP.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5395563/original/063153100_1761711808-ATK_Bolanet_BRI_SUPER_LEAGUE_BIG_MATCH__2_.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5144845/original/022421200_1740645722-Timnas_Indonesia_-_Trio_Calon_Pemain_Naturalisasi_Timnas_copy.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5362971/original/078040500_1758878372-Persita_Tangerang_Vs_Persib_Bandung.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5362119/original/035085500_1758837955-Calvin-Verdonk-Europa-League.jpg)