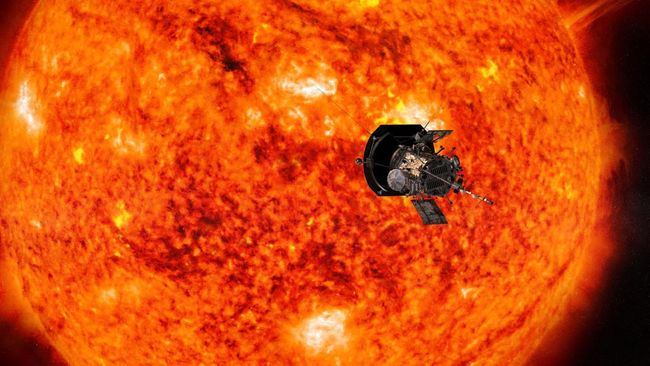Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pengumuman tarif 19 persen terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sempat mengejutkan banyak pihak. Namun dalam logika kebijakan, yang pada dasarnya selalu bermain dalam lapisan tersirat, angka tersebut justru dapat dibaca sebagai peluang strategis yang selama ini jarang disadari.
Alih-alih melihatnya sebagai kerugian sepihak akibat kebijakan dagang proteksionis Presiden AS Donald Trump, Indonesia semestinya menjadikan ini sebagai momentum korektif untuk membenahi struktur ekonomi nasional yang selama ini terlalu elitis, birokratis, dan jauh dari semangat kerakyatan.
Kesepakatan ini hadir sebagai bagian dari diplomasi perdagangan yang keras. AS memang memaksakan komitmen pembelian pesawat Boeing, energi, dan produk pertanian oleh Indonesia senilai lebih dari 20 miliar dolar AS. Namun Indonesia berhasil mencegah skenario buruk berupa tarif 32 persen yang sebelumnya mengancam produk ekspor unggulan seperti alas kaki, tekstil, kelapa sawit, karet, hingga udang.
Banyak yang memandang ini sebagai kompromi yang mahal, tapi sebenarnya justru inilah ruang diskresi kebijakan yang dapat dimanfaatkan untuk mereformasi ulang perekonomian dari bawah, yaitu dari desa, dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan dari koperasi produksi rakyat yang selama ini termarginalkan oleh sistem perdagangan besar.
Pada bidang respons kebijakan domestik, Bank Indonesia segera menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,25 persen. Ini sinyal penting yang menyatakan bahwa negara ingin menciptakan napas baru bagi ekonomi riil dan sektor produktif yang selama ini tertahan di balik ketergantungan terhadap konsumsi dan rente.
Lewat suasana ini, kita melihat peluang besar, yaitu jika ekspor produk utama harus bersaing dengan beban tarif, maka solusi satu-satunya adalah membangun rantai pasok dan kapasitas produksi yang efisien, adil, dan terdesentralisasi. Hal itu tidak akan lahir dari Jakarta atau Surabaya saja, melainkan dari ribuan desa dan komunitas usaha rakyat yang selama ini dipinggirkan.
Kita tentu tahu bahwa akses terhadap pasar global selama ini sangat elitis. Hanya pelaku besar dengan jaringan internasional, sertifikasi lengkap, dan relasi dengan birokrasi yang dapat menembus ekspor secara konsisten. Sementara pelaku kecil, petani unggulan, pengrajin, dan pelaku UMKM hanya menjadi rantai ke sekian dalam sistem perdagangan, yang penuh biaya siluman dan ketergantungan terhadap perantara.
Maka, dalam konteks tarif ini, sebenarnya ada ruang taktis: pemerintah bisa mendorong pemangkasan jalur distribusi dan reformasi izin ekspor agar lebih adil. Penguatan koperasi ekspor berbasis komunitas, pembentukan rumah produksi digital, hingga integrasi logistik dari desa ke pelabuhan besar harus segera dijalankan. Bukan sebagai program jangka pendek, tapi sebagai kebijakan struktural jangka panjang.
Bila kita tengok ke arah timur, Korea Selatan memberikan contoh yang sangat menarik. Negara tersebut tidak menjadi kekuatan ekspor hanya karena memiliki perusahaan besar seperti Samsung atau Hyundai, melainkan karena ia membangun ekosistem produksi dan pemerintahan dari bawah.
Sejak 1970-an, gerakan Saemaul Undong (Gerakan Desa Baru) menjadi model pembangunan berbasis komunitas yang menyatukan pembangunan infrastruktur dengan penguatan karakter dan etos kerja masyarakat desa. Jalan, irigasi, pusat produksi, hingga koperasi lokal dibangun dan dikelola dengan prinsip swadaya dan tanggung jawab bersama. Bahkan hingga kini, Korsel masih mempertahankan konektivitas desa-kota dalam logika ekonomi digital dan pemerintahan elektronik yang sangat transparan.
Tidak berhenti di sana, Korsel juga menjadi pelopor e-Government. Pelayanan publik, izin usaha, sertifikasi ekspor, hingga pendampingan UMKM terintegrasi dalam sistem digital nasional yang membuat desa-desa tetap kompetitif di tengah tekanan global.
Hal tersebut membuat pelaku ekonomi di Gyeonggi atau Jeolla memiliki peluang yang setara dengan yang ada di pusat kota Seoul. Bandingkan dengan Indonesia yang hingga kini masih mengandalkan sistem izin manual, birokrasi tumpang tindih, dan akses pasar yang sangat bergantung pada pusat kekuasaan ekonomi.
Di sinilah pentingnya menjadikan tarif Trump sebagai momentum. Bila kita bisa membentuk semacam "desa ekspor nasional" yang memiliki akses teknologi, pendampingan, fasilitas pembiayaan, serta jaringan logistik ekspor langsung, maka kita tidak lagi harus tergantung pada konglomerasi untuk menembus pasar global.
UMKM dan koperasi rakyat bisa mulai menjual alas kaki, kopi, furnitur, atau produk herbal langsung ke buyer global melalui sistem daring, dengan dukungan logistik berbasis digital dan sistem pembiayaan mikro yang inklusif. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Desa seharusnya mulai bekerja bersama, bukan sendiri-sendiri.
Karena pada dasarnya, ekspor tidak selalu harus dari kota. Justru jika desa dilibatkan, nilai tambah akan jauh lebih berlapis dan menyebar secara merata. Tarif 19% itu, jika dikelola dengan cara baru, justru bisa menjadi katalisasi lahirnya jaringan produksi berbasis komunitas yang memiliki daya saing, karakter, dan ketahanan.
Pemerintah hanya perlu dua hal: pertama, kemauan politik untuk menyederhanakan birokrasi ekspor dan membasmi rente yang selama ini menjadi tembok tinggi bagi pelaku usaha kecil. Kedua, keberanian fiskal untuk mengarahkan stimulus dan subsidi langsung ke desa-desa yang sedang bertumbuh, bukan ke pengusaha lama yang hanya bermain kuota dan relasi.
Sudah saatnya Indonesia belajar dari negara-negara seperti Korsel, yang membangun kekuatan ekonomi bukan dari tekanan, tapi dari ketegasan membangun dari bawah. Dalam bahasa ekonomi politik, tarif Trump ini tidak harus dilihat sebagai simbol ketimpangan, tapi sebagai pembuka pintu reformasi struktural yang selama ini tertunda.
Di tengah dunia yang makin multipolar dan pasar yang makin digital, Indonesia harus bergerak dari ekonomi eksklusif menjadi ekonomi partisipatif. Bukan hanya agar produk kita bisa tetap masuk pasar AS, tapi agar rakyat di desa-desa pun punya akses terhadap peluang yang sama. Karena sejatinya, pertumbuhan ekonomi sejati bukan yang terlihat di papan saham, tetapi yang terasa di dapur rumah tangga.
Jadi, kita tak perlu takut pada angka 19%. Yang lebih menakutkan adalah jika kita terus mempertahankan struktur ekonomi yang hanya berpihak pada yang besar. Karena dunia sedang berubah, dan yang bertahan bukan yang kuat, melainkan yang adaptif. Maka inilah saatnya: tarif sebagai peluang, rakyat sebagai pelaku, dan desa sebagai pusat pertumbuhan.
(miq/miq)













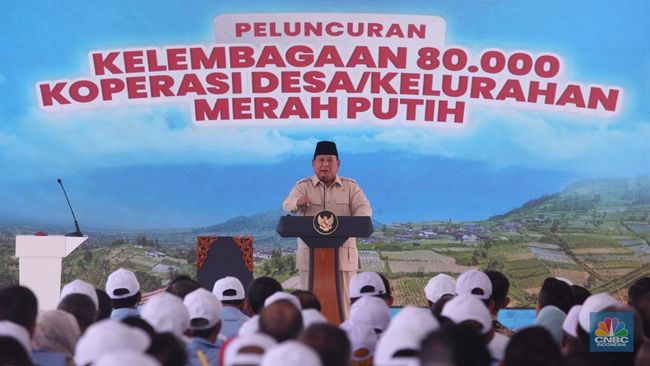

















:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5188944/original/032874400_1744718583-Timnas_Indonesia_U-17_-_Dafa_Al_Gasemi__Putu_Panji__Evandra_Florasta__Fadly_Alberto__Zahaby_Gholy_copy.jpg)




:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5180577/original/074787500_1743783583-GntCIvSaMAEfkgV.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/bola/watermark-color-landscape-new.png,1125,20,0)/kly-media-production/medias/5174282/original/018416500_1742913304-20250325BL_Timnas_Indonesia_Vs_Bahrain_Kualifikasi_Piala_Dunia_2026-05.JPG)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5170044/original/092559400_1742564635-Kualifikasi_Piala_Dunia_2026_-_Timnas_Indonesia_Vs_Bahrain_-_Ver_2_copy.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5200569/original/016450500_1745737981-Artikel_10_tahun_Bola.com_-_10_Pesepak_bola_lokal_terbaik_di_Liga_1_dalam_satu_dekade_terakhir_periode_2015_-_2025_copy.jpg)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2945074/original/009749200_1587463586-PSSI.jpg)



:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/bola/watermark-color-landscape-new.png,1125,20,0)/kly-media-production/medias/4767835/original/025515100_1710008044-083A0426.jpg)